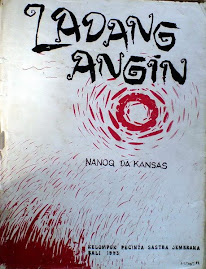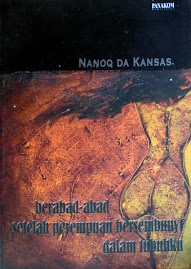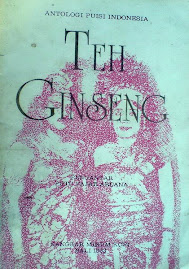29 August, 2008
lalu dia datang juga, ais. Kereta
malam itu – pluitnya yang getir
mengisyaratkan jarak yang akan mengirim
percakapan kita pada garis hitam putih
jalanan. Lalu
sejenak waktu akan hampa
andai aku selembar daun pohonan surabaya
yang dijatuhkan nasib di permukaan kalimas
maka akulah perjalanan panjang itu
kelelahan menjadikanku sempurna
memerankan lelaki. Berabad-abad
setelah perempuan bersembunyi dalam tubuhku
ajaib. Bau hutan – bau lautan
yang terbakar gemuruh kota
kutemukan menjadi hujan di matamu
lalu
subuh di kemarau jiwaku
berkemas menerima cahaya pertama
bagi sebuah musim tak bernama
Kategori PUISI
dapatkah engkau jelaskan, manisku
kereta inikah yang terlalu cepat
bergerak? Merengkuh pulau demi pulau
menjaring seluruh mimpi bagai laba-laba
atau kotamu yang bergegas menghapus jejak?
lalu di manakah cinta kita, ais?
sungguh. Aku ingin sekali memberikannya
kepada sebagian nasib yang mengendap
di tangan mungil dan lunglai
para pejuang anak-anak bermata sendu
sepanjang halaman parkir, lantai dasar plaza
ruang tunggu stasiun sampai ke kedalaman
pelabuhan perak yang berkeringat
selalu
dapatkah genggaman tanganmu kupinjam?
sejenak saja bagi pencarianku yang naif
setelah reruntuhan masa silam kita
membelukar membentuk nganga jurang demi
jurang yang membelah wajah siang
wajah malam
atau rambutmu yang masih panjang
bolehkah kuminta selembar saja?
kujadikan jembatan menuju cakrawala
pulang kepada peradaban yang rendah hati
Kategori PUISI
melengkapi percintaan kita yang sederhana
kukirim kepadamu sebuah sungai
mata airnya kuminta dari bintang di gunung
setelah ia ajarkan padaku
kejujuran langit membagi cuaca
untuk memberi nama musim demi musim
bumi kita yang jenaka
lalu muaranya kugali di pasir pantai
sebagai tanda keterbatasan
pengenalan kita pada pesisir takdir
yang disimpan ombak setelah angin
mengantar mimpi-mimpi
pada kesamaran tangis-tawa
begitulah kucairkan tubuh-hatiku
menempuh keteguhan batu-batu
menyelami kesetiaan riwayat daun
yang gugur menjadi susu bumi
kembali ke sumsum ibu
dan engkaulah ibu, karena
engkau melayarkan bintang
tanpa takut terdampar di pasir hitam
pantaiku yang tak selalu bening
Kategori PUISI
dan kita mencintai tanah air ini
apa adanya, ais. Meneladani ketulusan ibu
saat membasuh telapak kaki pahlawannya
di hari pertama ia tersentuh
gairah bumi gairah langit.
kita akan menanam sesuatu di sini
entah bunga atau duka.
jangan menangis di tepi jalan
bila engkau saksikan pohonan terluka
atau banyak wajah kehilangan bentuk
angin tak selalu membawa sejuk
ada kalanya ia tak dapat menolak
gemuruh dan badai
yang menggeliat dan bangkit tiba-tiba
dari jiwa-jiwa kekuasaan
abad yang cemas.
dan kita adalah pohon bagi angin
ditumbuhkan dengan bahasa terbatas
santun melepas daun
patah ranting sebelum ranum
biji di dalam daging.
jangan menangis. Cintaku padamu
akan senantiasa hidup seperti
cinta kita pada tanah air ini
yang sepenuhnya hanyalah ibadah
seluruhnya adalah karunia
kita perankan sesederhana rumput
yang mengerjakan rumah bagi serangga malam.
Kategori PUISI
(membaca koran terbakar)
ibukota rupanya telah menumpahkan
tinta buram dalam kertas-kertas suratmu
tanganmukah yang gemetar? atau
hurup-hurup itu sengaja disayat-potongi
untuk memagari ketenteraman semu
yang mereka tumbuhkan di koran-koran
televisi dan buku agenda.
aku nyaris mengerti, kekasihku
ini pelajaran sederhana tentang diam
yang tersesat di ruang kuliah kita
yang mesti kita pahami
seperti kita memahami cahaya pagi
yang berhak menghapus mimpi-mimpi kecil
dalam kelembaban rumah-rumah kardus
sepanjang perbatasan ibukota.
memegang suratmu, aku teringat catatan-catatan
dalam laci di sebuah meja kerja
: keputusan nomor berapakah
yang boleh kita tunda atau pertanyakan?
tidak! tak ada jarum jam yang
diciptakan untuk menunggu sebuah pertimbangan
dan atas sebuah pertanyaan kecil yang lugu
kisi-kisi tangsi akan dengan gembira
mengutuk kepala kita menjadi kambing hitam
atas tersandungnya persekutuan
antara topeng-topeng kebenaran dengan
laras sepucuk senapan.
membaca suratmu, kekasihku
aku segera paham
ibukota dalam kemegahan hatiku-hatimu
telah ditumpahi tinta buram
dari darah hurup-hurup yang disayat
yang dipotong
sebelum dideretkan dalam halaman sejarah
yang wajib dihapal anak-anak kitaesok pagi.
Kategori PUISI
26 August, 2008
untuk adikku: laurencia
aku akan merindukanmu nenek
senantiasa. tapi aku tak bisa
menangis sejujur air matamu
karena penderitaanmu adalah garam
dan cuka dunia, sedangkan kesepianku
lebih menyerupai iklan lampu hias
dalam televisi hitam putih
aku akan merindukamu nenek
senatiasa. tapi aku telah kehilangan
kegembiraan setulus air matamu
karena engkau danau
bagi air mata dunia
sedangkan aku lebih teka-teki
dari arus dan angin laut
bila engkau puisi, aku pun
barangkali puisi. hanya saja abjad
dalam darah dan doamu begitu utuh
sementara tanda baca di sekujur tubuhku
tak akan mampu menjelaskan
makna paling sederhanadari bahasa manusia
Kategori PUISI
suaramukah yang datang padaku
merambat dari angin, dalam cahaya
tergenang embun di bibir kelopak bunga?
ah, aku mengigau
menggapai-gapai benang terentang
di antara tempurung kepala dan jiwaku
menggapai-gapai tepian
di antara hasrat dan penolakanku
:aku rindu padamu ...
di luar, pagi pecah
berserakan jadi daun-daun kering dan jatuh
dari jendela, kulihat tubuhku gemetaran
memegang sapu hitam dan angker
menggorek-gorek sampah yang selalu saja tersisa
plastik-plastik, debu-debu
kertas-kertas koran yang tak terbaca
surat-surat cinta yang merana dan menggigil
kamus-kamus yang senantiasa tak terpahami
kulit-kulit pohon yang mengelupas
semuanya berwarna hitam
sehitam sapuku
dan ketika semuanya kubakar
asap itu pun berwarna hitam
berbau hitam: d a r a h!
darah siapakah yang mengalir sepagi ini?
aku ingin mengadu,
: aku tak membunuh!
aku sungguh-sungguh tak membunuh siapapun!
hari ini alangkah inginnya aku berdamai
alangkah inginnya aku diam
tapi aku telah melihat bom-bom berjatuhan
dan salah perhitungan tentang sasarannya
aku telah melihat
pestisida, insektisida, fungisida
diam-diam menyelinap ke setiap pori-pori udara
aku telah melihat cairan-cairan aneh
meresap dan bergolak ke rahim bumi
wahai! kenapa semua jadi punya hasrat bunuh diri?
sepagi ini kita telah bertengkar
: tentang nasib, kita tak bisa bicara! – ujarmu
aku mau mengalah, tapi korban terlanjur banyak
siapa yang mesti aku percayai?
terus terang saja, pada diri sendiri pun
aku acap kali tak percaya.
aku tak percaya ada hukum yang punya hati dan jiwa
aku tak percaya ada hukum yang bijaksana
seperti mereka yang telah merancang dan menulisnya
sebab hukum seperti sapu hitamku
: hitam dan angker
dan ketika hukum itu jatuh di alengka, kurusetra
hiroshima, tian an men, bagdad, bosnia, yerusalem
santa cruz, jakarta, aceh, maluku
di rumah tetangga dan di kamar tidurku
maka sampah-sampah mengeluh
: aku tak bisa menghindar ..., – bisiknya pada sejarah
dan dari jendela aku saksikan hujan
tak turun pada musimnya
pepohonan tak berbuah pada musimnya
anak-anak ke sekolah tanpa bakal pemahaman
bagaimana semestinya mencintai dan menghayati
jiwa hurup-hurup dan angka-angka
wahai! sepagi ini kita telah bertengkar
dengan kata-kata yang tak bisa lagi dimengerti
walau sepatah
sementara di luar jendela, aku melihat tubuhku
bergumul dengan jutaan bayang-bayang hitam
tubuhku yang telah kehilangan bentuk
terbanting-banting dan mengelupas
terakhir, aku lihat jutaan pagi dan daun-daun
kering berhamburan dari pecahan kepalaku
berjuta-juta bayangan hitam itu
kini sepanjang jalan menyapu dengan sapu hitamnya
dan segala air mata telah terbakar
asapnya hitam
berbau hitam: d a r a h!
Kategori PUISI
bermula cinta pada batas mana sebuah musim menyerah
aku merekah dari tatapan fajar
dan aku tak memilih tanah air
sebab aku sendiri
telah basah terguyur tempias musim
aku merekah jadi rindu
pada sekepak demi sekepak sayap kekupu
dan aku telah merasa tahu untuk sebatas pengertian
ketika kubiarkan taburan pelangi sarat warna
menerpa sejuk dari ujung cahyamu
kutangkap itu
bersama angin yang menjadi harumku
namun jika masih tersisa beberapa celah
antara ujung jemarimu dan penggalan daunku
aku mengerti itu
sebagaimana pula kupahami
ada tepi yang tak sampai diusap ombak
kuasaku hanya pesisir
Kategori PUISI